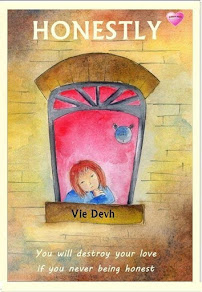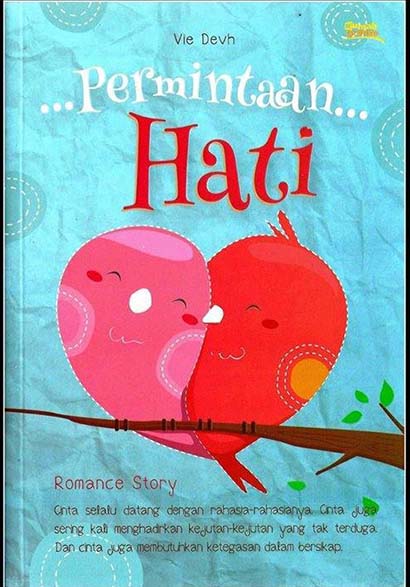KOMPAS, 13 Apr
2012. K. Bertens, Guru Besar Emeritus Unika Atma Jaya, Jakarta
Beberapa waktu lalu dalam rubrik ”Klasika”
Kompas edisi 5 Maret 2012 dimuat artikel singkat, ”Etika Berbicara di
Telepon”. Di situ dijelaskan bagaimana operator telekomunikasi di perusahaan
harus menjalankan tugasnya. Misalnya, ia tidak boleh bicara dengan nada tinggi.
Nada bicara harus selalu dijaga dan tetap tenang. Sebagai pembuka percakapan,
ia harus mengucapkan salam dan menyebutkan namanya kepada lawan bicara. Sebelum
menutup pembicaraan, ia tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih kepada lawan
bicara, dan seterusnya.
Tidak disangkal, semua petunjuk itu berguna dan malah
penting karena penampilan seorang operator telepon untuk sebagian menentukan
”wajah” perusahaan bagi dunia luar. Namun, tidak benar bahwa hal-hal itu
menyangkut etika. Petunjuk-petunjuk tadi bicara tentang etiket saja, bukan tentang etika. Mestinya penulis memakai judul
”Etiket Berbicara di Telepon”.
Seperti sering terjadi, di sini pun etika dicampuradukkan
dengan etiket. Padahal, dua pengertian itu sangat berbeda: etika mengacu ke
ranah moral, sedangkan etiket mengacu ke ranah sopan santun. Memang benar, ada
alasan juga mengapa etika dan etiket sering disamakan. Pertama, bentuk kedua
kata itu dalam bahasa Indonesia sangat mirip, seolah-olah yang satu hanya
sekadar variasi dari yang lain. Kedua, dan lebih penting lagi, baik etika
maupun etiket mengandung norma bagi tingkah laku kita.
Menurut etiket, kita sebagai pegawai perusahaan tidak boleh
berbicara dengan pelanggan di telepon dengan nada tinggi atau dengan cara tidak
sabar. Menurut etika, kita tidak boleh berdusta melalui telepon (ataupun dengan
cara lain). Dalam dua contoh ini etiket dan etika memberi norma tentang
perilaku yang sama, tetapi dari sudut pandang yang sangat berbeda.
Etiket menyoroti baik-buruknya perilaku dalam arti sopan santun.
Etika menyoroti baik-buruknya perilaku dalam arti moral.
Di sini tentu tidak dimaksudkan bahwa segi sopan santun
tidak penting dalam pergaulan di masyarakat. Hanya mau dikatakan bahwa segi
moral jauh lebih penting lagi. Mengapa demikian? Karena etiket hanya memandang
manusia dari luar, sedangkan etika menilai manusia dari dalam dengan melihat ke
dalam hatinya. Misalnya, kita menyaksikan bagaimana seorang koruptor melalui
pembicaraan di Blackberry-nya dengan pejabat pemerintah merencanakan suatu usaha
korupsi besar-besaran. Perilakunya sangat sopan. Berulang kali kita dengar,
”Ya, Pak”, ”Tidak, Pak”, ”Terima kasih, Pak” dengan nada halus dan hormat.
Namun, bagaimana dari sudut etika? Walaupun kita tidak mengerti isi pembicaraan
karena orang itu terus pakai kode, pada kenyataannya perilakunya sangat tidak
etis.
Barangkali sekarang sudah jelas mengapa etika dan etiket
tidak boleh dicampuradukkan. Kalau kita lakukan begitu, kita bisa membuat
kesalahan fatal dalam menilai tingkah laku orang. Banyak penipu berhasil dalam
melakukan kejahatan justru karena berlaku sangat halus dan sopan. Sambil
sepenuhnya memenuhi norma etiket, orang tetap bisa munafik. Etiket bisa menjadi
kedok untuk menyembunyikan perbuatan yang tidak etis sekalipun. Dalam konteks
etika, hal itu tidak mungkin.
KOMPAS, 30 Mar
2012. Taufik Ikram Jamil, Sastrawan Berbahasa Ibu Melayu Riau
Bagaimana perasaan Anda jika sesuatu yang Anda miliki
tiba-tiba asing, padahal dari segi fisik, benda tersebut tak berubah sama
sekali, bahkan Anda masih menyandang sebutan sebagai pemiliknya? Orang Melayu
Riau memiliki pengalaman mengenai hal ini dari berbagai segi. Tak saja
berkaitan dengan ekonomi dan politik, juga bahasa.
Ringkas cerita, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu
Riau. Kenyataan ini tentu saja menyebabkan tak sedikit orang Melayu Riau di
bawah ambang sadarnya beranggapan bahwa bahasa Indonesia juga bahasa Melayu
Riau. Tepat sekali yang dikatakan Sapardi Djoko Damono, salah seorang bintang
sastra Indonesia, dalam bukunya bahwa besar kemungkinan hanya orang Melayu Riau
dan Jakarta saja yang telah menjadikan bahasa Indonesia bahasa ibu sejak kecil.
Cuma tentu saja, banyak hal yang membedakan antara Melayu
Riau dan Jakarta ketika berhadapan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.
Pasalnya, dalam diri Melayu Riau, ketika menggunakan bahasa Indonesia, ada
perasaan kepemilikan asal. Tak demikian halnya bagi orang Jakarta yang
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dengan latar belakang
keragaman.
Sekarang bayangkan saja diri Anda sebagai orang Melayu Riau
yang sedang membaca koran atau majalah. Bagaimana perasaan Anda ketika bertemu
dengan kata seronok dalam lembaran yang sedang Anda baca. Dalam bahasa
Melayu Riau, seronok berarti sesuatu yang menyenangkan, sementara
dalam media yang Anda baca mengarah pengertian pada pornografi.
Mungkin juga Anda menemukan frasa sumpah serapah
yang dalam bahasa Indonesia cenderung bermakna sebagai suatu keadaan tindakan
berkaitan dengan marah. Namun, dalam bahasa Melayu Riau, kumpulan dua kata itu
berhubungan dengan jampi-jampi. Kalau berhubungan dengan marah, sebutannya
adalah sumpah seranah. Jadi, keduanya dibedakan oleh satu fonem:
antara -p- dan -n-, serapah–-seranah.
Alkisah, banyak lagi contoh yang dapat disebutkan. Namun,
contoh-contoh tersebut sudah memadailah menunjukkan arah perkembangan bahasa
Indonesia yang tak merujuk pada asal bahasa Indonesia itu sendiri. Hal semacam
ini juga terjadi pada memasukkan serapan baru dalam bahasa Indonesia yang
mengesampingkan bahasa asalnya, termasuk bahasa daerah lain—tentu saja perlu
tulisan tersendiri untuk memperkatakannya.
Sebagai orang Melayu Riau, apa yang Anda lakukan berhadapan
dengan kenyataan ini, apalagi kalau Anda seorang penulis? Pasalnya, di Riau
sendiri, akhirnya kebanyakan orang mengikuti arus penggunaan kata-kata yang
maknanya tak sesuai dengan kata asalnya dan menjadi bahasa ibu Anda dengan
tujuan agar dapat dipahami. Di sisi lain, Anda menolak keadaan tersebut dengan
alasan-alasan kebahasaan itu sendiri baik ditinjau dari psikologi maupun sosial,
disadari atau tidak.
Antara Indonesia Melawan Qatar
Lampung
Post, 21 Mar 2012. Kiki Zakiah Nur, S.S.
Menonton pertandingan sepak bola sebenarnya bukan kegemaran
saya. Tetapi, demi menemani suami yang menggemari sepak bola, saya ikut
menyaksikan pertandingan sepakbola kesebelasan Indonesia melawan Qatar yang
disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun televisi swasta beberapa waktu
lalu. Pertandingan babak pertama berakhir seri dengan kedudukan masing-masing
2.
Sebelum diselingi jeda iklan, reporter olahraga mengatakan
kalimat yang bunyinya begini, “Baik, pemirsa. Jangan ke mana-mana. Kita
saksikan pertandingan berikutnya antara Indonesia melawan
Qatar setelah iklan yang berikut.”
Pemakaian pasangan antara…, melawan…,
dengan contoh kalimat seperti itu sangat sering digunakan oleh reporter atau
wartawan olahraga pada acara pertandingan sepak bola. Secara sepintas memang
sepertinya tidak ada yang salah pada kalimat tersebut.
Namun, jika kita amati lebih lanjut, akan tampak
kesalahannya. Kesalahannya adalah penggunaan kata antara yang
dipasangkan dengan kata melawan.
Dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memiliki
pasangan tertentu. Salah satunya kata antara yang berpasangan dengan dan.
Kata antara dipasangkan dengan melawan tidak tepat. Jadi, seharusnya kalimat
yang diucapkan oleh reporter olahraga tadi adalah: “Baik, pemirsa. Jangan ke
mana-mana. Kita saksikan pertandingan berikutnya antara Indonesia dan
Qatar setelah iklan yang berikut.”
Selain dengan kata melawan, kata antara
juga sering dipasangkan dengan kata dengan, misalnya pada kalimat:
Ternyata ada perbedaan yang sangat jelas antara keinginan saya dengan
kenyataan yang saya hadapi. Pasangan antara… dengan… pun
salah. Kalimat itu harus diperbaiki menjadi kalimat: Ternyata ada perbedaan
yang sangat jelas antara keinginan saya dan kenyataan yang
saya hadapi.
Pasangan kata lain yang juga sering digunakan secara salah
adalah baik… ataupun… seperti pada kalimat: Baik
yang tua ataupun yang muda harus bisa menahan emosi. Pasangan kata baik
adalah maupun. Kalimat itu seharusnya menjadi: Baik yang tua maupun
yang muda harus bisa menahan emosi.
Contoh lainnya adalah tidak…, melainkan
dan bukan…, tetapi. Kedua pasangan kata itu mempertentangkan
dua hal, yakni mengingkarkan sesuatu dan mengiyakan yang lain. Yang diingkarkan
oleh kata bukan ialah benda. Oleh sebab itu, untuk mengiyakannya harus
digunakan kata yang cocok untuk kata benda, yaitu kata melainkan.
Sementara itu, yang diingkarkan oleh kata tidak adalah kata selain
kata benda, yakni kata kerja dan kata sifat. Jadi, kata yang tepat untuk menyatakan
kebalikan kata kerja dan kata sifat adalah tetapi. Dengan demikian,
pasangan yang benar adalah tidak…, tetapi… dan bukan…,
melainkan… seperti pada kalimat: Gadis itu tidak cantik, tetapi
menarik. Dan kalimat: Dia bukan kakak saya, melainkan saudara
sepupu saya.
Media massa memang bisa menjadi alat pembelajaran yang
sangat baik bagi masyarakat. Reporter atau wartawan di media massa mana pun
memiliki peranan yang sangat besar dalam pembinaan berbahasa pada masyarakat.
Pemakaian bahasa yang tepat dalam media massa adalah guru
yang paling berpengaruh dan akan memiliki dampak yang positif dalam pemakaian
bahasa masyarakat. Sebaliknya, jika bahasa dalam media massa kacau, akan
memberikan pengaruh yang negatif, terutama bagi mereka yang tidak tahu akan kaidah
bahasa.
Rumah Sang Pendeta
Majalah Tempo,
19 Mar 2012. Putu Setia, Nama baptis Ida
Pandita Mpu Jaya Prema Ananda
Beberapa hari sebelum saya dibaptis sebagai pendeta pada
2010, ada ritual yang jelimet di rumah tinggal saya. Rumah saya dinaikkan
“statusnya” menjadi griya. Ini sebutan tempat tinggal yang dianggap
suci, karena penghuninya tak lagi tergoda urusan duniawi. Begitulah formalnya.
Saya sempat bergurau: “Di Jakarta saya pernah tiga tahun
tinggal di griya.” Banyak orang tertawa dan ada yang menuduh saya “tak
tahu aturan”. Tapi saya ngotot: “Ya, betul, saya tinggal di Griya
Wartawan Cipinang Muara.” Orang menjadi maklum setelah saya jelaskan itu
kompleks perumahan wartawan.
Griya atau kadang ditulis geriya
memang untuk tempat tinggal para Brahmana, pendeta di kalangan umat Hindu.
Banyak aturan yang dikenakan, baik untuk penghuninya maupun untuk tetamunya.
Dari mana istilah itu berasal? Orang langsung menyebut
Sanskerta. Maklumlah, pendeta Hindu akrab dengan bahasa Sanskerta karena semua
mantra pemujaan memakai bahasa itu. Sanskerta adalah bahasa Weda (Veda).
Dalam bahasa Sanskerta–kalau memang itu asal-usulnya–kata
itu ditulis grhya dengan huruf “r” berisi titik di bawahnya.
Bagi orang yang memahami Sanskerta, huruf “r” dengan titik di bawahnya
dibaca “ri” sehingga grhya harus dibaca grihya.
Namun orang Melayu yang tak mempelajari bahasa yang tak dipakai sebagai bahasa
pergaulan itu lebih condong membaca dengan grahya, bahkan graha.
Ada Kamus Sanskerta-Indonesia karangan Dr Purwadi
dan Eko Priyo Purnomo (keduanya pengajar di UGM Yogya) yang menyebutkan ada
kata griya dalam bahasa Sanskerta yang berarti: rumah, wisma. Namun
kamus ini dalam kata pengantarnya sudah merancukan bahasa Sanskerta dengan
bahasa Kawi (Jawa Kuno), seolah-olah kedua bahasa itu sama.
Dalam Kamus Jawa Kuno-Indonesia susunan L.
Mardiwarsito ditemukan kata grha (juga dengan huruf “r”
memakai titik di bawahnya) dan diberi arti rumah. Grha (Jawa Kuno
versi Mardiwarsito) ini lebih mirip dengan grhya (Sanskerta). Tapi grhya
tidak berarti rumah, melainkan: suatu desa atau perkampungan dekat kota (antara
lain di Kamus Sanskerta-Indonesia karya I Made Surada, lulusan S-2
Sanskerta Universitas Allahabad, India).
Yang hendak saya katakan adalah kata-kata yang muncul
belakangan, apakah itu ada di bahasa daerah (lokal) atau bahasa nasional,
banyak menyerap kata yang ada dalam bahasa sebelumnya. Bisa jadi griya
yang dipakai dalam bahasa Indonesia saat ini adalah serapan dari grha
(Jawa Kuno) dan grhya (Sanskerta).
Boleh jadi pula, kata graha yang banyak digunakan
saat ini untuk arti yang sama, yakni rumah atau wisma, adalah serapan yang
“salah paham soal bunyi”.
Dalam hal umat Hindu tetap memakai griya untuk
rumah pendeta (padahal jika mengacu pada Sanskerta artinya tak pas) barangkali
mewarisi kesalahpahaman ketika kata itu diserap ke Jawa Kuno. Harap dipahami,
bahasa Kawi pun menjadi bahasa ritual umat Hindu–selain bahasa untuk seni
sakral.
Tapi bisa pula pemakaian kata griya itu dengan
kesadaran memasukkan kiasan–sebagaimana kekhasan orang Bali yang tecermin dalam
bahasa daerahnya–karena para Brahmana di masa lalu memang harus dekat dengan
kota karena mereka menjadi Bhagawanta (penasihat) kerajaan.
Kalau begitu halnya, saya berpikir sederhana, biarkan saja
kata serapan itu dipakai apa adanya sesuai dengan kenyataan saat ini. Jadi,
biarkan griya tetap dipakai sesuai dengan bunyi versi Sanskerta, sementara
graha juga tetap dipakai dengan arti yang sama: rumah atau wisma.
Masalahnya adalah kata graha nyata-nyata ada dalam
bahasa Jawa Kuno yang berarti buaya, sehingga Bina Graha adalah tempat untuk
membina para buaya.
Namun berapa banyak pemakai bahasa Jawa Kuno saat ini? Kata
graha sudah dianggap “bukan buaya”. Selain ada Bina Graha, ada Graha
Pena (gedung Jawa Pos), Lila Graha (wisma pemda Bali di Bedugul), dan banyak
lagi. Begitu pula kata griya sudah mulai “tak suci lagi”, istilah ini
dipakai oleh banyak pengembang. Bahkan di Bali sendiri ada hotel dan perumahan
memakai nama griya, padahal di sana tak ada pendeta yang tinggal.
Menyederhanakan serapan kata Sanskerta yang rumit itu
sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu tanpa ada masalah. Para pengamat mencatat,
sudah sekitar 800 kata Sanskerta diserap ke bahasa Melayu dengan pengucapan
versi Melayu.
Kita kadang lupa kalau payudara itu berasal dari kata payodhara
(Sanskerta). Mungkin kita agak rikuh memakai kata yang lahir dari kiasan: buah
dada.
Komedian?
KOMPAS, 16 Mar
2012. Kurnia JR, Cerpenis
Sekarang ada sebutan yang lebih populer bagi
seniman panggung pengocok perut: komedian. Istilah pelawak mulai
ditinggalkan tanpa alasan jelas kecuali kecenderungan masyarakat yang mudah
terkesima oleh kosakata keinggris-inggrisan. Ini gejala peyorasi dalam linguistik.
Dalam hal ini, kata pelawak mengalami degradasi semantik.
Peminjaman atau penyerapan kosakata dari bahasa asing
adalah situasi alamiah dan wajar dalam suatu bahasa. Yang celaka jika proses
itu berakibat pembonsaian khazanah bahasa kita sendiri. Kosakata asing diserap
seraya merendahkan derajat makna padanannya yang sudah ada dalam bahasa kita
tanpa urgensi sama sekali.
Apabila orang berpikir bahwa comedian memiliki
spesifikasi makna yang lekat dengan konteks profesi, sesungguhnya begitu juga pelawak.
Sejak TVRI berdiri dan menghibur kita, banyak sudah bermunculan pelawak atau
grup lawak, yakni orang atau sekelompok orang yang pekerjaannya melucu, baik
dengan alur cerita maupun berupa sketsa. Sekadar contoh, ada Srimulat, BKAK,
Warkop Prambors (Warkop DKI), dan Jayakarta Group.
Sesungguhnya terminologi pelawak tak terasing dari
kompetensi intelektual individual—jika itu yang dianggap tidak ada oleh mereka
yang melebih-lebihkan istilah komedian di atas pelawak dewasa ini.
Kita memiliki Bing Slamet, Eddy Soed, Bagyo, Gepeng, Teguh
(Srimulat), Dono-Kasino-Indro, dan lain-lain yang tak melucu dengan kepala
kosong. Saat diwawancara wartawan, mereka mampu mengekspresikan penghayatan
artistik sekaligus intelektual atas profesi mereka. Saat berbicara sebagai
pelawak, mereka mengungkap sisi intelek yang dingin dan berjarak sehingga orang
pantas tercengang menyadari bahwa dalam kelucuan mereka tersembunyi keseriusan
profesional yang tak main-main.
Mungkin orang melongo kagum pada sejarah seni drama Barat
yang berasal dari Yunani Kuno berupa tragedi dan komedi. Dari situ berkembang
seni pertunjukan modern dalam aneka bentuk. Apa yang disebut comedian
dalam seni pertunjukan modern Barat pun tak lagi terpatok pada makna pelakon
sandiwara jenaka bertendensi filosofis. Kini motifnya hiburan belaka: sekadar
berbagi keriangan dengan lelucon ringan. Secara historis itulah yang juga
terjadi pada seni pertunjukan kita.
Dalam seni pertunjukan tradisional seumpama ketoprak,
ludruk, topeng Betawi, wayang kulit dan golek, terselip humor, parodi,
sindiran, kritik sosial, lelucon, dagelan. Wayang kulit yang notabene
bertendensi filosofis dengan ajaran moral adiluhung bahkan memberi tempat
khusus bagi para punakawan, tokoh-tokoh bijak di jagat wayang dengan tampang
rakyat jelata yang naif dan kocak.
Seni pertunjukan humor mengiringi dinamika sosial kita ke
bentuk yang sekarang. Tiada tuntutan bahwa lawakan harus meramu kritik sosial,
apalagi mengemban elemen filosofis yang ”tidak praktis” pada masa ini.
Pelawak adalah profesi yang sejajar dengan penyanyi,
musisi, pemain sinetron, sutradara, dan lain-lain di dunia hiburan dengan
sejarah panjang seni pertunjukan sebagaimana comedian di negeri
asalnya.
Hemat Perlu Cermat
Lampung
Post, 14 Mar 2012. Chairil Anwar, Alumnus FKIP Jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah Universitas Lampung
Jika dalam artikel-artikel sebelumnya banyak dicermati
tentang pemborosan dan kemubaziran
kata yang seharusnya dihindari, tulisan kali ini akan membahas tentang
penghematan satuan bahasa yang justru harus dihindari karena tidak sesuai
dengan aturan kebahasaan.
Penghematan dilakukan untuk menciptakan tuturan atau
tulisan yang efektif. Namun, kita sebagai pemakai bahasa jangan terlalu over
dalam menyingkat, bahkan menghilangkan suatu unsur kebahasaan. Alhasil,
alih-alih ingin menciptakan komunikasi yang efektif, bahasa yang digunakan
justru meyimpang dari kaidah kebahasaan.
Tuturan atau satuan bahasa yang lazim digunakan oleh
pemakai bahasa terkait dengan penyingkatan yang keliru di antaranya pada kata
“pom bensin”, “promo”, “rinci”, “optimis”, “bra”, “relawan”, dan lain-lain.
Pada bentuk “pom bensin” terdapat kekeliruan pada salah
satu unsurnya, yakni “pom”. Bentuk sebenarnya ialah “pompa”. Memang tidak dapat
dimungkiri bahwa pemakai bahasa umumnya mengucapkan “pom bensin”, tapi
hendaknya kita tetap menggunakan bentuk yang benar: “pompa bensin”. Memang
terkesan janggal, karena kita sudah terbiasa dengan kesalahan itu.
Kemudian, kita kerap melihat spanduk, papan iklan, brosur, atau
media iklan lainnya yang menggunakan kata “promo” berukuran besar untuk merayu
konsumen membeli produk atau memakai jasa penyedia iklan tersebut. Ternyata,
bentuk “promo” juga merupakan kekeliruan terkait dengan penyingkatan kata.
Dalam pemasangan iklan, space atau ruang
memang perlu dipertimbangkan untuk menekan biaya. Namun, alangkah baiknya jika
kita tetap menggunakan bentuk yang sudah dibakukan ketimbang mengorbankan
bahasa Indonesia yang benar.
Menggunakan kata “promosi” tentu lebih menunjukkan kita
sebagai bangsa yang bangga akan bahasa nasionalnya. Jangan sampai kesalahan
berjamaah ini semakin mengesankan bentuk yang salah itu seolah-olah benar.
Pada kata “rinci” kita bahkan telah salah sampai pada
bentuk turunanya, yakni “rincian”. Dalam KBBI tidak ada lema
“rinci”, yang ada ialah “perinci”. Dengan demikian, bentuk turunannya yang
benar ialah “perincian”.
Sama seperti kesalahan pada bentuk “rinci”, bentuk “bra”,
“optimis”, dan “relawan” pun tidak terdapat dalam senarai KBBI.
Kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang telah dibakukan ialah “braseri”,
“optimistis”, dan “sukarelawan”.
Sebelum kita semakin larut dengan kesalahan-kesalahan
serupa, sebagai pemakai bahasa hendaknya kita harus lebih cermat dan teliti
dalam menggunakan kosakata. Untuk itu, dalam memahami aturan kebahasaan, kita
harus sedikit demi sedikit memahami aturan tersebut secara keseluruhan.
Alhasil, overgeneralisasi akibat dari kekurangsempurnaan pemahaman terhadap
bahasa yang baik dan benar dapat diminimalisasi.
Hafalan Shalat Delisa
Lampung
Post, 7 Mar 2012. Suheri, Guru SMAN Sukadana, Lampung Timur
Hafalan Shalat Delisa adalah judul film berdasar novel karya Tere Liye. Film
tersebut berkisah tentang seorang gadis cilik yang periang bernama Delisa.
Perawan kencur itu berasal dari Desa Lhok Nga, Aceh Timur. Saat tsunami melanda
Aceh, 26 Desember 2004, pada saat yang sama Delisa akan mengikuti ujian praktik
salat yang ia pelajari.
Kemudian, tsunami mengubah jalan hidupnya. Delisa terpisah
dari keluarganya, kakinya mengalami cedera saat gelombang air itu datang.
Beruntung ia ditemukan oleh prajurit Smith saat pingsan. Kaki Delisa kemudian
diamputasi dan dalam tenda penampungan korban bencana pascatsunami ia menjadi
inspirasi dan penyemangat hidup bagi sesama korban bencana itu.
Tulisan ini tidak bermaksud mengomentari film tersebut,
tetapi secara khusus akan membahas gugus konsonan /sh/ yang digunakan dalam
kata “shalat” pada judul film tersebut. Selain kata “shalat”,
kita kerap menjumpai (dalam bahasa tulis) gugus konsonan /sh/ yang digunakan
dalam kata seperti shahur, shalawat, shubuh, shahih, shaf, dan
lain-lain sebagai kata dari serapan bahasa Arab yang seolah-olah bergugus
konsonan /sh/.
Penggunaan gugus konsonan /sh/ itu perlu dicurigai akibat
dari analogi adanya gugus konsonan /kh/, seperti dalam kata khalayak, khalifah,
khalik, khamar, khas, khawatir, khazanah, dan lain-lain sebagai kata serapan
dari bahasa Arab bergugus konsonan /kh/. Pertanyaan yang muncul, benarkah
analogi tersebut?
Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (TBBI) Edisi III (2008) menyebutkan bila dua konsonan terdapat dalam satu suku
kata yang sama (suku kata KKV), konsonan pertama terbatas pada konsonan hambat
/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, dan konsonan frikatif (bunyi desis) /f/, /s/,
sedangkan konsonan keduanya terbatas pada konsonan /r/ atau /l/, /w/, /m/, /n/,
/t/, /k/.
Menyoal konsonan frikatif /s/, gugus konsonannya adalah
/sl/, /sr/, /sw/, /sp/, /sm/, /sn/, /sk/, /st/, /sf/ seperti pada kata slogan,
sriwijaya, swalayan, spora, smokel, snobisme, skala, status, sferoid.
Gugus konsonan /sh/ pada contoh kata serapan asing itu
diserap dari huruf “shad” huruf ke-14 abjad Arab. Konsonan itu dianggap sama
dengan konsonan /kha/, huruf ke-7 abjad Arab. Karena /kha/ terdapat gugus
konsonan /kh/, hal ini diperlakukan sama pada konsonan /sh/ huruf “shad”
sehingga terjadilah penulisan kata serapan bahasa Arab tersebut yang
sesungguhnya menyalahi kaidah TBBI, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
III (2005), penulisan kata shalat, shahur, shalawat, shubuh, dan shahih ditulis
tanpa konsonan /h/ karena memang frikatif /s/ bahasa Indonesia tidak atau belum
mempunyai gugus konsonan /sh/.
Hal ini dipertegas oleh Ratih Rahayu yang menyimpulkan
bahwa dari sekian banyak kata yang berawalan huruf /s/ dalam KBBI, tidak ada
satu pun kata yang berawalan /sh/, (lihat Ratih Rahayu dalam Laras
Bahasa: Fobia Bahasa Indonesia, hlm. 76, Kantor Bahasa
Provinsi Lampung, 2008).
Sehingga shalat, shubuh, dan shahih jika
ingin memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar seharusnya ditulis
salat, sahih, dan subuh.
Kesalahpahaman atau ketidakhirauan terhadap penggunaan tata
bahasa, ejaan, dan penulisan unsur serapan dari bahasa asing tampaknya sudah
mengakar kuat dalam diri masyarakat Indonesia. Sehingga, untuk mewujudkan pemakaian
bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bangga berbahasa Indonesia masih
berupa jalan yang sangat panjang.
Bahasa Indonesia sebagai Cermin?
Majalah Tempo, 20 Feb 2012. Berthold Damshauser, Kepala
Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Bonn; Pemimpin Redaksi
Orientierungen, dan redaktur Jurnal Sajak
Suatu hari pada jam mata kuliah bahasa Indonesia di
Universitas Bonn, Jerman, kami berdiskusi tentang penerjemahan. Saya memberikan
tugas kepada para mahasiswa untuk memahami dan menerjemahkan teks berita di
sebuah harian Indonesia yang bukan saja mengandung kesalahan tata bahasa, tapi
ditulis demikian kacau alias mengabaikan logika kalimat. Setelah 10 menit, para
mahasiswa begitu putus asa dan menyatakan mogok.
“Pak, teks ini tak dapat kami terima. Sajikan dong teks
yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak ada, kami
mohon kuliah ini digunakan untuk membahas tema lain. Bukankah telah lama Bapak
berjanji menyampaikan renungan Bapak tentang perkembangan bangsa Indonesia?“
Merasa bersalah telah memilih teks yang tak bermutu–padahal
memang itulah yang saya peroleh dari kebanyakan harian di Indonesia–saya
menjawab: “Indonesia adalah bangsa muda yang telah mencapai kemajuan yang
mengagumkan. Negara-bangsa RI, yang terdiri atas ratusan suku bangsa, sudah
mencapai kesatuan yang kukuh dalam suasana demokratis, dan semakin berhasil
mewujudkan prinsip keadilan, termasuk keadilan sosial. Bahkan dalam hal
pendidikan dan teknologi….“
“Maaf, Pak,“ tegur sebuah suara, “mungkin lebih menarik
bila Bapak kaitkan dengan bahasa. Misalnya, sejauh mana bahasa Indonesia jadi
cermin perkembangan atau perubahan budaya Indonesia!”
“Baik,” jawab saya santai. “Tapi apa maksud Anda dengan
‘bahasa sebagai cermin’?”
“Begini, Pak, misalnya penyerapan kosakata asing yang
terjadi pada abad lampau. Apa kira-kira kesimpulan Bapak jika mengamati kata
serapan seperti politik, demokrasi, presiden, parlemen,
konstitusi, republik, legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Apakah telah terjadi westernisasi bahasa Indonesia?
Apakah itu seiring dengan westernisasi pemikiran. Soalnya, kata-kata tadi bukan
kata sembarangan, kata-kata itu menyangkut dasar-dasar kenegaraan.“
“Westernisasi pemikiran? Jangan gegabah menyimpulkan. Itu
cuma dampak penjajahan, juga di bidang bahasa. Bahasa Belanda ikut menjajah
hingga kata-kata tadi, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin atau Yunani,
ditanam paksa di tubuh bahasa Indonesia. Jangan lupa, itu cuma kata, tak
berarti bangsa Indonesia kurang mandiri dalam menemukan konsep dan jati diri!”
“Saya setuju, Pak!” kedengaran suara mendukung. “Bapak
betul. Itu hanya istilah. Orang Jerman dulu juga dipaksa menyerap
kata-kata Latin atau Yunani, termasuk kata demokrasi. Hal ini tidak
berarti orang Jerman langsung demokratis. Tak jarang, kata cuma baju, cuma
topeng. Contoh sebaliknya tentu ada, misalnya kata serapan yang populer
di Indonesia: korupsi.“
Wah, saya senang punya mahasiswa sepandai itu. Apalagi
muncul suara dukungan berikutnya: “Saya juga setuju, Pak! Khususnya apa yang
Bapak sebut jati diri dan kemandirian itu. Sebab, setelah westernisasi
kosakata, bahasa Indonesia mulai haus akan kata serapan dari bahasa lain,
khususnya bahasa Jawa yang feodal itu. Sehingga ada istilah seperti tut
wuri handayani, prinsip mulia yang dulu suka diterapkan ABRI. Ada juga bina
graha, tempat mukim seorang presiden yang berpedoman pada aja kagetan atau
mikul dhuwur mendhem jero. Ketika presiden itu mengundurkan
diri–resminya: berhenti–istilah yang dipakai adalah lengser keprabon alias
turun takhta, seolah-olah ia seorang raja. Barangkali ia memang lebih
seperti seorang raja daripada presiden. Tapi, ya, kalau begitu, bahasa juga
cermin sesuatu….”
“Iya,” saya mencoba bersikap arif, “segala sesuatu selalu
mungkin. Apakah ada komentar atau tambahan dari yang lain?“
“Saya, Pak! Andai bahasa itu cermin, apa yang kira-kira
dapat disimpulkan dari gejala terbaru bahasa Indonesia, yakni makin banyaknya
kata serapan Arab?”
“Penggunaan dan penyerapan kosakata Arab wajar saja,” jawab
saya. “Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Wajar kalau muslim di Indonesia
berkiblat pada bahasa itu. Telah ratusan tahun itu terjadi. Sama seperti umat
Katolik yang tetap menghargai bahasa Latin sebagai bahasa sakral.“
“Tapi, Pak, arabisasi bahasa Indonesia yang terjadi itu
bukan pada istilah teologi, melainkan pada pembicaraan sehari-hari, misalnya
sapaan afwan atau ukhti. Bahkan kata ibu mulai
diganti dengan umi!” demikian sang mahasiswa kembali bertanya.
“Lho, bagus kan! Daripada mummy,
lebih menarik umi,“ saya mencoba bergurau untuk melunakkan suasana.
Percuma, serangan semakin jadi:
“Pak, saya kira rekan mahasiswa berhak diberi jawaban
serius. Apa Bapak ragu akan peranan bahasa sebagai cermin? Apa Bapak tak merasa
perlu memikirkan kemungkinan bahwa arabisasi kosakata bahasa Indonesia adalah
penanda zaman, cermin arabisasi budaya Indonesia? Andai itu yang terjadi,
adakah pengaruhnya pada toleransi orang Indonesia dalam beragama? Apa itu akan
diganti oleh dogmatisme ala (Saudi-)Arab?”
Ngawur kan, pertanyaan
begitu. Tak sudi kujawab! Tiba-tiba lonceng berbunyi, jam kuliah sudah selesai.
‘Kamseupay’
Lampung
Post, 15 Feb 2012. Febrie Hastiyanto, Bloger, peminat bahasa media sosial
Awal tahun 2012 ditandai dengan kembali populernya akronim
“kamseupay” di media sosial kita. Kabarnya akronim ini pernah populer
pada tahun 1980-an, bersamaan dengan lahirnya bahasa gaul kala itu semacam “doski”,
“kawula muda” atau “yoi”—sebelumnya lema “yoi” diucapkan “yoa”,
misalnya dapat kita simak dalam percakapan di seri-seri film Catatan Si Boy
(Cabo).
Akronim dan kata bahasa gaul remaja Ibu Kota kala itu
produktif diintroduksi antara lain melalui corong radio Prambors
Jakarta. Kamseupay secara umum dipanjangkan menjadi “kampungan sekali uh
payah”, sejumlah variasi tafsir kamseupay lahir seperti “kampungan
sekali udik payah”, atau menganggap kamseupay sebagai kata, bukan
akronim. Kalangan yang menganggap kamseupay sebagai kata umumnya
mengartikannya sebagai “kampungan”.
Baik dimaknai sebagai kata maupun akronim, kamseupay
bertitik tolak pada kata “kampungan”. Kampungan sendiri menurut KBBI daring
diartikan sebagai ‘berkaitan dengan kebiasaan di kampung, terbelakang (belum
modern), juga kolot’; serta dapat juga diartikan sebagai ‘tidak tahu sopan
santun, tidak terdidik, atau kurang ajar’.
Sudah tentu makna ini bersifat konotatif dan tidak selalu
merepresentasikan karakteristik penduduk yang tinggal di kampung yang sering
disinonimkan dengan desa dan dusun. Secara administratif, kampung merupakan
satuan wilayah pemerintahan terkecil di bawah kecamatan dengan kata generik
desa. Dari empat arti lema “kampung” dalam KBBI, salah satunya diartikan
sebagai kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang
berpenghasilan rendah).
Ketika digunakan sebagai media komunikasi, bahasa bersifat
etis. Artinya, selain memiliki makna denotatif, bahasa—dalam hal ini
kata—memiliki makna konotatif. Dalam konteks lema “kampung”, konotasi atau
nilai rasa kebahasaan yang ada celakanya semua bersifat negatif, meskipun
konotasi memungkinkan nilai rasa kebahasaan yang positif.
Makna paling netral dari lema “kampung” bersifat denotatif,
yakni kata untuk menyebut satuan administrasi dan wilayah di Tanah Air.
Berbeda dengan antonimnya, makna lema “kota” menurut KBBI
justru secara relatif memiliki konotasi positif, misalnya sebagai wilayah yang
penduduk di dalamnya bergiat di sektor industri, atau mencerminkan kebudayaan
dan pemikiran internasional (kosmopolitan).
Makna konotatif kampung dan kampungan sebagai tidak tahu
sopan santun, tidak terdidik, dan kurang ajar sesungguhnya dapat berlaku kepada
siapa saja, bahkan lebih banyak diidap oleh orang kota, sebagai antonim orang
kampung. Pada praktiknya, pewarisan nilai-nilai, filsafat kehidupan, maupun
tradisi justru berlangsung lebih intensif pada orang kampung. Meskipun makna
kampung lebih banyak bersifat konotatif-negatif, tampaknya orang kampung lebih
banyak bersikap cool. Kalau orang kampung disebut sebagai kampungan,
mungkin pikir mereka: dasar kamu kekota-kotaan!
Sesuatu
Lampung Post, 8 Feb
2012. Dian Anggraini.
“Selamat Lebaran ya, semoga bisa menjadi sesuatu,
Alhamdulillah bisa jadi sesuatu di bulan Ramadan ini.” “Sesuatu enggak menurut
kamu?”
Bisakah Anda menebak kutipan kalimat siapakah itu? Saya
yakin, dari anak kecil hingga orang tua bisa menjawab pertanyaan ini. Penutur
tersebut pasti Syahrini, mantan teman duet Anang Hermansyah yang kini
fenomenal.
Demam Syahrini kini menjangkiti masyarakat kita. Tidak
hanya eksistensi berbusananya yang ditiru, gaya bicara juga menjadi tren. Kata
“sesuatu” begitu populer. Rekan-rekan selebritas Syahrini pun mulai ketularan
dan latah mengucapkannya saat disorot kamera.
Ia mengaku banyak orang yang mengikuti kata “sesuatu.”
Namun, salah menggunakan kata tersebut dalam kalimat. Lalu, ia pun mengajari
bagaimana cara memakai kata “sesuatu” yang benar menurutnya. “Kalau habis
dandan aduh cantiknya, sesuatu banget,” ujar Syahrini. Ia juga mencontohkan
bagaimana pengucapan kata sesuatu itu dilontarkan. “Harus lemah
gemulai ngomongnya,” kata Syahrini.
Selain “sesuatu”, kata “alhamdulillah” juga tak kalah
meledaknya. Saking populernya, sebuah penyedia layanan telekomunikasi
memintanya untuk menjadi catatan suara. “Saya diminta oleh salah satu provider,
karena banyak yang meminta dan mengunggah kata ‘Alhamdulillah yah, sebentar
lagi Lebaran dan Alhamdulillah yah, Lebaran tahun ini dapat THR’,” ujarnya.
Menurut saya, entah apa yang istimewa dari ungkapan yang
sering sekali diucapkan Syahrini ini. Sampai-sampai saat ini sudah menjadi buah
bibir di mana-mana. Rasa-rasanya kata sesuatu dan alhamdulillah bukanlah kata
yang asing untuk kita. Ah, mungkin (pikir saya), Syahrini publik figur
sehingga apa yang dikatakannya menjadi sorotan banyak orang.
Sebenarnya apa sih arti sesuatu sebenarnya. Mari
kita tengok Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Dalam kamus ini, sesuatu berarti barang atau hal yang tidak tentu
(untuk menyatakan benda yg kurang tentu). Contohnya sesuatu yang ada padanya
sangat dibutuhkan oleh orang lain.
Dari pengamatan saya di beberapa kalimat yang dilontarkan
Syahrini, sesuatu-nya bisa berarti baik atau bagus. Semisal ya,
alhamdulillah ya, berarti banyak orang senang dengan logat saya. Dan kata-kata
saya dianggap sesuatu. Namun, tak jarang pula “sesuatu” bermakna
abstrak. Contohnya semoga menjadi sesuatu banget.
Ini berbeda saat artis Peggy Melati Sukma memomulerkan kata
pusing. Pusing versi Peggy berarti ungkapan kalau dia memang
benar-benar pusing, di suatu kondisi atau pada lawan bicaranya. “Pusiiiiiingg…!”
ujarnya, dengan intonasi panjang dan centil.
Setiap sisi publik figur memang selalu menjadi
sorotan. Mereka menjadi contoh bahkan teladan masyarakat. Andai syarat menjadi
artis harus mampu berbahasa yang baik, niscaya bahasa Indonesia tidak begitu
abstrak di telinga kita. Semoga menjadi sesuatu. Salam.
‘Agama Sejati’ dan Celana Jins
Majalah Tempo, 30 Jan 2012. Rohman Budijanto, Wartawan
APA kira-kira reaksi publik kita ketika ada
secarik produk mode diberi merek “Agama Sejati”? Besar kemungkinan
akan gempar. Sulit terpikirkan bagaimana gaya berpakaian bisa diberi label
“Agama Sejati”. Tapi, dari kawasan dunia bebas, produk berlabel True Religion
ini malah sukses.
Saat masuk ke Indonesia, produk denim kelas atas karya
suami-istri dari Los Angeles, Jeffrey dan Kym Lubell, ini tidak menimbulkan
kehebohan. Salah satunya karena merek itu tak diindonesiakan, tetap True
Religion. Ada jarak psikologis berbahasa yang menjaga agar yang memakai merek
itu tidak dianggap sedang “mengamalkan agama sejati”.
Jika dicermati, ada banyak merek produk fashion dari
negara Barat yang kalau diterjemahkan bisa aneh sekali. Ada produk laris
berlabel Poison (parfum dari Christian Dior), Opium (parfum, Yves Saint
Laurent), Agent Provocateurs (lingerie, parfum), Envy Me dan
Guilty (keduanya parfum dari Gucci), Bathing Ape (produk fashion,
lengkapnya A Bathing Ape in Lukewarm Water, disingkat BAPE), atau Urban Decay
(mode).
Andaikan itu semua produk Indonesia, apa reaksi pasar
ketika ada merek-merek produk gaya hidup berlabel Racun, Opium, Agen
Provokator, Silakan Cemburu, Anda Bersalah, Monyet Mandi atau Monyet Mandi di
Dalam Air Suam-suam, dan Busuknya Kota? Tentu bagian pemasaran harus bekerja
lebih keras untuk meyakinkan pasar bahwa produk itu baik-baik saja, bahkan
berkelas premium.
Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa (negara) Barat yang
berekonomi mapan memang memiliki pengalaman dan perkembangan tersendiri.
Kebebasan, yang dibela melebihi agama, memungkinkan bahasa dimanfaatkan sejauh
mungkin, termasuk ke wilayah yang diejek dan disakralkan. Itu semua demi gaya
hidup, “agama” yang kini paling banyak pengikutnya, terutama di perkotaan.
Hebatnya, ketika masuk ke Indonesia, produk-produk bernama
“subversif” itu tak mengalami masalah. Kita tak pernah mendengar, misalnya,
kasus penolakan Opium dan Poison dalam pemeriksaan Bea dan Cukai. Padahal opium
dan racun biasanya menimbulkan masalah serius bagi pembawanya.
Tak hanya dari permainan makna, kadang nama merek diambil
dari ungkapan tabu yang dipermainkan. Misalnya produk SpEX Symbol dan FCUK,
yang juga top di dunia gaya hidup. Kuat sekali terkesan bahwa merek ini dibuat
agar orang menoleh ke arahnya karena refleks persepsi seksual. Setelah
mencermatinya, bisa jadi orang akan tersenyum. Kecele, tapi gemas.
Di Indonesia, merek lokal juga mulai mengadopsi ide “nakal”
seperti itu. Ketika baru diluncurkan, Es Teler 77 menimbulkan kernyit di dahi.
Apa kaitan es campur berbahan dasar santan, avokad, dan nangka ini dengan
“teler” alias mabuk? Ternyata tak ada. Itu hanya pilihan nama.
Di Yogyakarta ada Dagadu. Ini adalah kata prokem
dari “matamu”. Di sana, itu berarti umpatan. Tapi, setelah nama prokem
berlambang mata ini dijadikan merek aneka suvenir, terutama kaus, ternyata
sangat terkenal. Memang ada jarak psikologis yang membuat kata “matamu” terasa
empuk bila berbentuk prokem: Dagadu.
Di Surabaya juga ada “merek” kuliner yang jadi ikon: Rawon
Setan. Rawon ini diembel-embeli setan, konon, karena bukanya menjelang tengah
malam. Berbagai kalangan, termasuk para agamawan (lawan abadi setan), ternyata
menyukai makanan berbahan kuah hitam dan empal daging serta kecambah ini.
Peduli setan namanya, yang penting enak.
Fenomena lain, di mal juga ditemukan minuman Air Mata
Kucing. Orang mulai menerima produk mirip teh dari kelengkeng kering ini
setelah menepis anggapan sedang menyesap cairan dari mata kucing. Ada juga produk
distro Patahati bersimbolkan hati retak. Selain itu, ada resto Mbah Jingkrak,
berlogo nenek berkebaya sedang berjingkrak.
Tentu masih banyak produk kreatif bernama di luar kotak
kelaziman. Mereka menyerap anggapan negatif untuk memberi energi positif dalam
dunia komersial yang memerlukan kejutan.
Pabrik rokok telah mendahului memakai nama “sepele” yang
akhirnya jadi hebat. Djarum, Gudang Garam, dan Bentoel (bentul adalah sejenis
talas) bisa menjadi contoh.
Tentu saja produk sukses tak hanya mengandalkan nama aneh.
Nama keluar dari pakem hanyalah bahasa penggoda, agar orang menoleh ke produk
itu di tengah rimba persaingan. Selebihnya, kesuksesan ditentukan kualitas dan
penerimaan pasar.