Novel karya Adinda, penulis pertama yang menerbitkannya di Loka.
Dulu,
saya pernah menulis “Sejarah Didirikannya Penerbit Loka Media”,
sekarang saya ingin share pengalaman selama saya menjalani
usaha di bidang penerbitan. Sebenarnya sudah lama ingin menulisnya,
tetapi ... karena masih banyak job saya baru sempat
menuliskannya.
Menjalani usaha memang tidak selalu jalannya mulus, apalagi jika
perusahaan baru. Kita harus merintis dari bawah dulu, menikmati
proses sampai suatu saat benar-benar ada di puncak.
Buku pertama yang Loka terbitkan adalah When I Open My Eyes
dan I Miss You hasil dari event cerpen yang kami
adakan, sebenarnya itu adalah lomba cerpen yang saya adakan di
penerbit lain—sudahlah saya tak mau membahasnya lagi.
Pertama, masalah yang kami alami adalah mengenai ISBN. Entah kenapa
semenjak saya masuk jadi lini Pena House, ISBN keluarnya lama.
Biasanya paling lama satu minggu, ini sampai dua minggu.
Tapi tetap Alhamdulilah karena ISBN keluar.
Berhubung penerbit indie, dan kami baru berdiri. Loka memberikan
paket penerbitan Rp100.000 dulu. Tadinya ingin memberikan harga
200-300. Tapi takut kemahalan. Setelah posting paket penerbitan Loka
Rp100.000,-, kemudian ada yang komentar. Katanya terlalu murah,
biasanya yang murah itu tidak berkualitas. Gimana perasaan saya saat
itu ketika ada yang komentar seperti itu?
Tentu saja rasanya sakit. Niat baik memberikan paket penerbitan
murah, tetap saja ada yang tidak suka. Ya, memang sih niat baik tak
selalu disambut dengan baik juga. Akan selalu saja ada yang tidak
suka.
Klien pertama yang kami tangani
saat itu adalah penulis bernama Adinda Amara. Suatu kebanggaan bagi
kami karena kami mendapatkan klien di awal penulisnya ramah. Mau
diajak kerjasama.
Tentunya saya juga tambah senang
ketika Adinda sering curhat kepada saya mengenai kepenulisan. Membuat
saya semakin dekat dengannya. Dinda menerbitkan novel perdananya di
penerbit yang baru berdiri.
Dulu sempat tanya sama Dinda,
“Kenapa memilih Loka?
Loka kan baru berdiri, saat itu kami juga belum mengeluarkan cover
terbitan kami. Apa karena harganya yang murah?”
tanya saya.
Dinda menjawab, “Aku nerbitin
di Loka bukan karena harganya, Kak. Tapi saat melihat logo Loka, aku
langsung suka. Keren. Yang ada di pikiranku pasti nanti desain
cover-nya juga keren.”
Terima kasih lho, ya, sama Kak
Wulan Kenanga yang sudah membuat logo cantik. Ketjup. :*
Lalu
masalah kedua setelah ISBN, naskah yang katanya dicetak hanya
menghabiskan waktu 2 Minggu. Malah jadi 3 Minggu. Ditambah saat
pengiriman yang memakan waktu sebanyak 10 hari. Membuat saya rasanya
ingin berubah jadi monster.
Ribut-ributlah
saya dulu sama Pimpinan Pena House. Kesal karena buku belum
sampai-sampai. Kalau itu buku pesanan saya sih nggak masalah, tapi
ini pesanan orang lain. Ditambah karena dulu saya pernah trauma, 3
kali hasil cetak tidak memuaskan. Membuat saya semakin takut kalau
para pemesan akan kecewa.
Saya coba tenangkan Dinda dan
para pemesan yang lain, minta maaf. Untunglah mereka mengerti dan
menjawab, “Nggak apa-apa, Kak. Yang penting bukunya sampai dengan
selamat.”
Dan syukurlah, ketakutan dan
kesabaran saya menunggu kiriman buku cetak terbitan Loka hasilnya
memuaskan. Kertas awal yang saya bayangkan warnanya abu-abu seperti
koran, ternyata warnanya kuning seperti novel terbitan Gagasmedia.
Saya ikut bahagia ketika penulis
yang menerbitkan naskahnya di Loka saat memegang buku hasil cetaknya.
Rasanya seperti memosisikan diri sebagai penulisnya sendiri.
**
Berhubung
banyak yang memuji cover Loka bagus. Akhirnya saya menaikkan
paket penerbitan jadi 200ribu. Mengingat saya juga harus menggaji Kak
Wulan, Rizky dan Lisma.
Saya ketemu klien kedua, kali ini
penulisnya laki-laki. Dia sudah kirim naskahnya, dan saya serahkan
kepada Lisma untuk di-edit.
Tetapi, belum apa-apa penulis ini sudah meributkan cover.
Dia ingin cover-nya
buatan sendiri. Okelah, saya coba lihat dulu hasil cover-nya.
Kemudian saya dan Tim Loka pun kaget karena cover-nya
terlihat asal-asalan.
Berhubung penulis ini juga belum
bayar, saya sudah kasih no. Rekening, mengingatkan juga tapi cuma
diam saja. Yasudah, saya lepas penulis ini. Sudah ada perasaan nggak
enak. Saya yakin masih banyak yang mau menerbitkannya di Loka.
Dan benar saja, setelah seminggu
kemudian ada dua penulis yang minta no. Rekening saya untuk bayar
biaya penerbitan.
Dulu naskah Dinda, Lisma yang
edit. Tetapi berhubung Lisma sudah saya berikan naskah Pelangi
di Langit Mendung—cerpen yang dikembangkan jadi novel yang saya
tawarkan kepada Rositi untuk terbit gratis karena saya suka.
Kepala saya pusing saat mengedit
naskah yang EBI-nya kacau.
Naskah seterusnya yang saya edit
pun begitu. Akhirnya setiap Sabtu, saya dan Kak Wulan membuat program
#LOKABahasa, share Ejaan Bahasa Indonesia.
Saya sampai mengeluh saat itu
tidak mau lagi sistem bayar dan mau menggunakan sistem seleksi saja.
Kak Wulan menenangkan saya sekaligus menohok.
“Kamu tahu apa tujuan penerbit
indie didirikan?
Menerbitkan naskah yang belum dapat kesempatan terbit di mayor, Say.
Yang namanya kerja meski di bidang yang kita sukai, pasti ada saja
hambatannya. Semangat, ya. Jangan marah terus.”
Ya, benar. Saya tidak boleh
egois. Justru saya banyak belajar dari naskah-naskah yang belum bisa
dikatakan bagus hingga berhasil menyulapnya jadi naskah yang layak
untuk dibaca. Menyuruh penulisnya untuk revisi. Memberikan ilmu
tentang EBI. Karena sejak awal membuka penerbitan karena ingin
berusaha mementingkan kualitas. Dan saya juga sebaiknya hanya perlu
membayangkan wajah-wajah bahagia para penulis pemula ketika memegang
bukunya yang terbit di Loka media. Lalu pikiran saya tertuju pada
Dinda yang saat itu begitu bahagianya memposting foto novel Reach
Out to Me. Dia sampai mengucapkan banyak terima kasih pada Loka
dan bilang kalau tidak salah memilih penerbit untuk menerbitkan novel
pertamanya. Saya menyunggingkan senyum. Ikut terharu.
**
Ini
dia masalah selanjutnya yang membuat saya sempat patah semangat.
Masalah internal. Saat itu saya baru sampai kampus, ada BBM yang
masuk dari Rizky Dewi. Dia bilang, “Mbak, ada sesuatu yang pengin
aku omongin.”
Saya
balas, “Apa, Ky?”
Rizky balas BBM saya lama,
membuat saya dag dig dug. Dalam hati saya sudah ada perasaan nggak
enak. Pikiran saya Rizky pasti mengundurkan diri. Dan beberapa menit
terbuang ketika saya menunggu balasan Rizky Dewi, dugaan saya benar.
“Maaf Mbak, aku mau
mengundurkan diri dari Loka.”
Oh, Demi apa Rizky keluar?
Aset berharga saya keluar?
Karena apa?
Masalah apa?
Apa karena saya memberikan gaji yang tak seberapa hingga dia
memutuskan keluar?
“Aku lagi banyak tugas kuliah,
Mbak. Aku keluar bukan karena bayarannya, aku ikhlas bantuin Loka.
Aku cuma ngerasa nggak enak aja, soalnya pasti kalau desain
cover bakalan lama.”
Saya coba tenangin diri dulu.
Tarik napas. Saya nggak bisa melepaskan Rizky Dewi. Dia sudah masuk
dalam sejarah didirikannya Loka. Dia sudah saya anggap seperti
keluarga sendiri.
“Begini, Ky. Kalau memang kamu
lagi sibuk, nggak apa-apa kamu istirahat sementara dulu aja. Kamu
fokus nugas dulu aja. Loka nanti-nanti. Kamu desain sebulan juga
nggak masalah. Tapi jangan keluar, ya. Itu bukan solusi yang tepat.
Aku anggap kamu cuti aja. Jangan keluar. Loka baru berdiri, aku udah
anggap kamu kayak keluarga sendiri. Bantu aku merintis Loka bareng
Kak Wulan sama Lisma, ya?”
Rizky pun tak berapa lama
membalas BBM saya, yang sempat membuat saya dag dig dug dia tetap
ingin keluar.
“Makasih atas pengertiannya,
ya, Mbak. Aku jujur ngerasa nggak enak banget. Iya, itu pasti. Loka
udah jadi keluargaku. Oke, semangat!”
Alhamdulilah.
Rizky nggak keluar.
Tetapi beberapa hari kemudian...
Saya ribut-ribut dengan Lisma
Laurel karena kesal dia menyerah mengedit naskah yang saya suruh. Dia
juga akhir-akhir ini malas dan lebih suka mendesain. Saya saat itu
kasih pilihan, mau jadi editor
atau jadi desain cover?
Lisma tidak pilih dua-duanya.
Dia minta maaf dan memilih
mengundurkan diri.
Rasanya bagai ditimpa batu
raksasa.
Saya dengan sangat kecewa harus
melepaskan Lisma meski sudah menahannya untuk tidak keluar.
Kecewa. Marah. Bukan marah pada
Lisma. Tapi marah pada diri sendiri karena terlalu berharap pada
Lisma yang bahkan sudah saya anggap sebagai adik sendiri.
Saya langsung curhat sama Kak
Wulan.
“Lisma keluar.”
“Lho, kenapa?”
Saya jelasin bla bla bla.
Jawaban Kak Wulan malah membuat
saya tambah cengeng. “Sayang banget, padahal Lisma serba bisa.”
“Hmm,” gumam saya. “Apa aku
terlalu kasar, ya, Say?”
“Maybe.
Yaudah, nggak apa-apa kalau itu memang keputusannya.”
Saya juga bilang ke Rizky kalau
Lisma keluar. Dia menanyakan alasannya, saya jawab bla bla bla.
“Pasti ada faktor lain, Mbak.”
“Ya. Mungkin aku terlalu emosi,
kasar. Atau apalah. Aku udah terlanjur kesal, Ky. Takut menaruh
harapan besar dan percaya sama orang lagi.”
“Jadikan pelajaran saja, Mbak.
Biar nggak mudah mempercayai orang.”
Tapi meski saya sudah blokir akun
FB Lisma. Saya tidak pernah menganggap dia keluar dari Loka. Dia
tetap masuk dalam sejarah Loka. Dia tetap akan saya anggap sebagai
adik. Saya sebegitu marah, sangat kecewa karena sayang. Sudah
menganggap dia seperti keluarga sendiri.
Setelah itu, saya mencari
pengganti Lisma. Kak Idha Febriana. Saya juga cerita sebelumnya
mengenai Lisma.
“Kak, kalau mau mengecewakan
aku sekarang saja, ya. Bilang nggak mau gabung di Loka. Aku trauma.”
Semua pun kembali baik-baik saja.
Tetapi setelah itu masalah-masalah lain pun datang. Masalah yang
lebih besar. Membuat Loka Media berada di ujung tanduk.
“Kenapa, ya, dari awal buka
usaha kok Loka dapat masalah terus,” kata Kak Wulan sambil
menyelipkan emoticon :'(
“Allah hanya mengetes kita,
Say. Mau sungguh-sungguh atau nggak di bidang ini. Semangat. Allah
nggak mungkin ngasih masalah kalau nggak ada jalan keluarnya. Aku mau
sedia payung dulu sebelum hujan.”
:')
Bersambung...












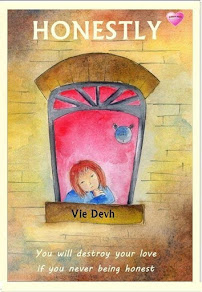
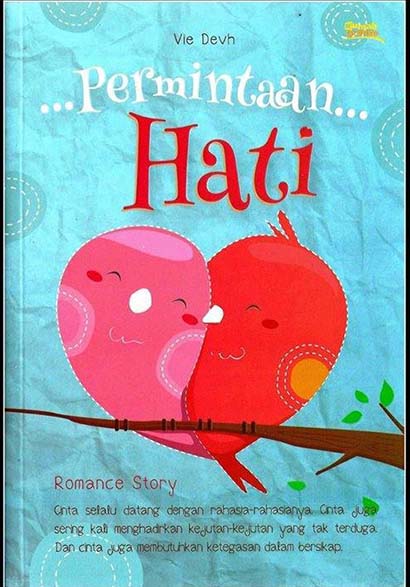


0 komentar:
Posting Komentar